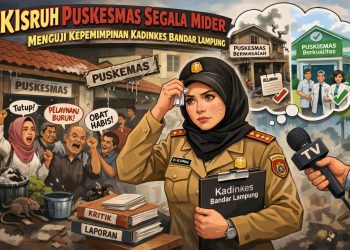Penulis: Penta Peturun
Stafsus Maneker RI
PANTAU LAMPUNG- Andai Pramoedya Ananta Toer masih hidup hari ini, mungkin akan menatap layar smartphone dengan pandangan yang sama tajamnya ketika ia mengkritik kolonialisme Belanda di Bumi Manusia. Disaksikan bukanlah lagi tuan tanah dan pribumi, tapi algoritma dan driver ojek online. Sebuah bentuk penindasan baru yang lebih halus namun tak kalah kejam.
Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism menggambarkan bagaimana kapitalisme kontemporer tidak lagi sekedar mengeksploitasi tenaga kerja, melainkan mengubah pengalaman manusia menjadi data yang dapat dipanen dan dijual. Slavoj Žižek melengkapi kritik ini dengan konsep “ideologi cyber-fetishisme”. Bagaimana teknologi menyembunyikan hubungan eksploitasi di balik narasi kemajuan dan efisiensi. Sementara Antonio Gramsci memberikan kerangka memahami bagaimana hegemoni baru terbentuk melalui “common sense” digital yang menormalisasi prekarisasi kerja.
Di Indonesia, konvergensi ketiga perspektif teoretis ini terwujud nyata dalam kalkulasi data aktif dan pasif nasib 4,2 juta driver ojek online. Menurut data BPS 2024, yang berjuang memperoleh pengakuan sebagai buruh, bukan mitra bisnis seperti yang diklaim platform digital. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan hanya beberapa driver ojol yang terdaftar sebagai peserta mandiri, sisanya bekerja tanpa jaminan sosial apapun. Ironisnya, di tengah perjuangan ini, Presiden Prabowo Subianto punya kuasa, rada memaksa kepada aplikator menunjukkan sikap pada hari raya Idul Fitri 1446. Memberikan “bonus hari raya” mengambil jalan tengah ditengah gencar pertanyaan fundamental tentang status ketenagakerjaan.
Žižek dan Kesadaran Palsu yang Tercerahkan. “Aku Tahu, Tapi…”
“Tuan, saya tahu iseorang driver ojol berbicara kepada Pramoedyani bukan kemitraan yang sebenarnya,” demikian mungkin , “tapi apa yang bisa saya lakukan? Harus tetap kerja buat makan anak-anak.” Inilah yang oleh Slavoj Žižek disebutkan sebagai “enlightened false consciousness”, kesadaran palsu yang tercerahkan. Mereka tahu persis bahwa dirinya dieksploitasi, namun tetap terjebak dalam sistem karena tidak ada pilihan lain.
Žižek melihat platform ojol sebagai manifestasi sempurna dari fetishisme komoditas digital. Setiap hari, sekitar 4,2 juta driver online turun ke jalan dengan kesadaran penuh bahwa mereka bukan “mitra bisnis” seperti yang diklaim platform. Mereka tahu bahwa tarif terus dipotong, jam kerja tanpa batas, risiko kecelakaan ditanggung sendiri, dan beberapa dari mereka yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Namun mereka tetap mengendarai sepeda motor, membuka aplikasi, menunggu notifikasi order. “Saya tahu platform tidak peduli keselamatan saya, tapi bagaimana lagi?” karena platform adalah mesin digital, tidak punya rasa dan nurani. Inilah formula Žižekian yang sempurna. Mereka tidak bodoh atau naif, mereka hanya terjebak dalam struktur yang tidak memberikan alternatif. Platform digital menciptakan ilusi pilihan sambil merampas kemungkinan pilihan sesungguhnya.
Žižek akan mengkritik keras narasi “ekonomi berbagi” sebagai ideologi murni. Ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyebut driver ojol sebagai “pekerja digital yang harus dimanusiakan, bukan algoritma data dalam status kemitraan” seperti pernyataan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer (Noel) pada sidang ILO di Jenewa Juni 2025. Itu adalah pengakuan bahwa selama ini mereka diperlakukan sebagai extension dari mesin, bukan manusia dengan martabat.
Keputusan Bersejarah ILO, Pengakuan yang Terlambat
Dalam sidang International Labour Conference di Jenewa Juni 2025, dunia menyaksikan momen bersejarah ketika ILO memutuskan bahwa driver ojol bukanlah “mitra bisnis” melainkan “pekerja digital” yang berhak mendapat perlindungan penuh sebagai buruh. Keputusan ini akan ditetapkan menjadi Konvensi ILO pada 2026, mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
8 (delapan) bulan sudah Noel menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, bulat tekad berangkat dalam sidang tersebut. Jauh sebelum sidang Jenewa dimulai, Noel menyampaikan pernyataan yang akan tercatat dalam sejarah, bukan rekomendasi tapi harus Konvensi yang diusung pemerintah Indonesia karena “Ojol adalah manusia yang harus dimanusiakan, bukan algoritma data dalam status kemitraan.” Kata-kata ini, sederhana namun revolusioner, menggemakan semangat humanisme yang selalu diperjuangkan Pramoedya.
Namun, Pramoedya yang cerdas akan bertanya, mengapa pengakuan ini datang begitu terlambat? Mengapa harus menunggu jutaan jiwa terjerembab dalam ketidakpastian sebelum dunia internasional mengakui kemanusiaan mereka? “Terpenting saat ini negara hadir”, itu yang selalu disampaikan Prabowo. Data World Bank menunjukkan bahwa ekonomi platform di Indonesia bernilai $27 miliar, namun sebagian besar keuntungannya mengalir ke kantong korporasi multinasional, sementara para driver hidup dari hari ke hari.
Gramsci akan melihat keputusan ILO ini sebagai hasil dari “war of position” yang panjang. Perjuangan merebut makna dan definisi dalam ruang diskursif internasional. Selama bertahun-tahun, platform membangun hegemoni melalui redefinisi kerja sebagai “kemitraan,” namun perlawanan dari serikat buruh global akhirnya berhasil meruntuhkan narasi tersebut.
Angka-angka yang Berteriak. Ketika Data Membongkar Kebohongan
Pramoedya selalu percaya bahwa kebenaran terletak pada kehidupan rakyat kecil, bukan pada retorika penguasa. Data kalkulasi umum 4,2 juta pengemudi ojol dan pasif. Data lebih nyata dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menuturkan total 2 juta pengemudi ojol yang aktif di Indonesia, saat ini baru 250 ribu pengemudi yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga masih ada sekitar 1,75 juta yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Jadi itu bukti bahwa negara hadir di dunia para pekerjanya, 1,7 juta teman-teman kita di luar sana belum terlindungi JKK JKM.”
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ojol bisa mendapatkan jaminan jika terjadi kecelakaan. Selain itu, selama tidak bekerja, peserta akan tetap menerima pendapatan bulanan. Ini masuk dalam program Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
BPS mencatat rata-rata pendapatan driver ojol Rp 2,1 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional di sebagian besar kota. Namun yang lebih menyakitkan, mereka harus menanggung sendiri biaya operasional, bensin, servis motor, helm, jaket, bahkan handphone untuk menjalankan aplikasi. Setelah dipotong biaya operasional, pendapatan bersih mereka rata-rata hanya Rp 1,4 juta—angka yang membuat Pramoedya akan berteriak, “Inilah wajah sebenarnya kemerdekaan digital!”
World Bank dalam laporan 2024 menyebut ekonomi platform Indonesia bernilai $27 miliar dan terus tumbuh 35% per tahun. Tapi siapa yang menikmati pertumbuhan ini? Bukan para driver yang bekerja 12-14 jam sehari, melainkan para pemegang saham platform yang duduk nyaman di gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan kantor pusat di Singapura atau Amerika.
Pengemudi Ojol bekerja berdasarkan “terms and conditions” aplikasi yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Ini bukan kemitraan. Ini adalah bentuk baru dalam istilah perbudakan modern dengan bungkus teknologi.
Politik Kedermawanan, BHR Tanpa Mengubah Struktur
“Saya imbau ditambahlah,” kata Presiden Prabowo ketika mendengar driver ojol menerima bonus hari raya (BHR) sekitar Rp1 juta. Bahkan ada yang hanha menerima 50 ribu, miris lagi tidak menerima sama sekali. Kalimat sederhana ini mengungkap seluruh kontradiksi pendekatan baru. Berkedermawanan di permukaan, namun problem pelik struktural terus akan mendapat solusi. Sebagai mana amanah konstitusi.
Pramoedya akan melihat ini sebagai cerminan mentalitas priyayi yang dikritiknya dalam Bumi Manusia memberikan belas kasihan kepada rakyat kecil seolah sambil mempertahankan sistem yang menindas mereka. BHR untuk driver ojol adalah charity capitalism dalam bentuknya yang paling telanjang. Memberikan bantuan untuk menutupi ketidakadilan sistemik tanpa mengubah struktur yang menyebabkan ketidakadilan tersebut.
Žižek akan menyebut ini sebagai “ideology at its purest”, ketika kekuasaan beroperasi paling efektif melalui tindakan yang tampak progresif namun sesungguhnya konservatif. Memberikan BHR tanpa mempertanyakan mengapa 3,7 juta driver ojol tidak memiliki hak dasar sebagai pekerja untuk mendapat THR secara otomatis.
Yang lebih ironis, ketika 71 organisasi buruh dan driver ojol memberikan rekomendasi tentang perlindungan pekerja platform digital, respons aplikator adalah memberikan bonus, bukan pengakuan status. Ini adalah trasformismo ala Gramsci, mengakomodasi tuntutan rakyat dalam bentuk yang tidak mengubah hubungan kekuasaan fundamental.
Meski Indonesia turut mendukung keputusan ILO di Jenewa Juni 2025 yang mengakui driver ojol sebagai pekerja digital, implementasi domestiknya masih jauh panggang dari api. Keputusan bersejarah tersebut seperti akan menjadi slogan kosong jika tidak diikuti dengan perubahan regulasi konkret di tingkat nasional.
Bumi Manusia versi Digital.
Dari Cultuurstelsel ke Algoritma
“Pribumi itu seperti kerbau,” kata seorang tokoh Belanda dalam Bumi Manusia, “hanya mengerti perintah dan cambuk.” Kini, lebih dari seabad kemudian, algoritma platform digital berperan sebagai cambuk baru yang tak terlihat namun lebih efektif. Driver ojol tidak dicambuk secara fisik, namun didisiplinkan melalui rating, suspend akun, dan manipulasi orderan.
Dalam tetralogi Bumi Manusia, Pramoedya menunjukkan bagaimana Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) menciptakan hierarki yang memposisikan pribumi sebagai kelas terbawah. Hari ini, platform digital seperti Gojek dan Grab menciptakan hierarki serupa dengan membungkusnya dalam narasi “kemitraan” dan “fleksibilitas kerja.” Bedanya, jika dahulu penjajah mengambil rempah-rempah dan hasil bumi, kini platform digital mengambil data dan pengalaman hidup.
Driver ojol, sebagaimana digambarkan Zuboff, bukan hanya memberikan jasa transportasi. Mereka menjadi sumber data perilaku yang sangat berharga. Pola pergerakan, preferensi konsumen, waktu kerja optimal, hingga respons terhadap insentif. Data ini kemudian diolah menjadi “behavioral futures”, prediksi perilaku yang dapat dijual kepada pengiklan dan pihak ketiga lainnya dengan nilai triliunan rupiah.
“Mereka tidak sekedar mengambil tenaga kita,” mungkin akan berkata seorang driver kepada Pramoedya, “tapi juga mengambil jejak kehidupan kita, pola hidup kita, bahkan cara kita berinteraksi dengan kota.” Inilah kolonialisme data, eksploitasi yang lebih halus namun lebih mendalam daripada kolonialisme fisik.
Yang lebih ironis, eksploitasi ini dilakukan dengan membuat korban merasa “berdaya.” Platform mempromosikan narasi “jadilah bos untuk diri sendiri” sambil membangun sistem kontrol yang lebih ketat daripada hubungan kerja konvensional. Setiap gerakan dipantau GPS, setiap interaksi dinilai rating, setiap penolakan order dicatat sebagai “pelanggaran.”
Perjuangan Merebut Kemanusiaan. War of Position di Era Digital.
“Tuan,” begitu mungkin seorang driver ojol berbicara kepada Pramoedya, “mereka bilang kami mitra, tapi kenapa kami diperlakukan seperti babu? Kenapa rating menentukan hidup-mati kami? Kenapa kami tidak boleh pilih orderan yang jauh?”
Perjuangan driver ojol untuk diakui sebagai buruh bukan sekadar soal status hukum. Ini adalah perjuangan untuk merebut kembali kemanusiaan mereka dari cengkeraman algoritma. Pengakuan sebagai buruh berarti hak atas upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Hal-hal yang secara sistematis dinafikan melalui label “mitra bisnis.”
Gramsci akan melihat perjuangan ini sebagai “war of position”, perebutan makna dan definisi dalam ruang diskursif. Selama bertahun-tahun, platform digital berhasil membangun hegemoni melalui redefinisi kerja sebagai “kemitraan,” namun keputusan ILO di Jenewa Juni 2025 menandai kemenangan besar dalam perang wacana ini. Ketika dunia internasional mengakui bahwa driver ojol adalah “pekerja digital,” bukan “mitra bisnis,” ini adalah keretakan fundamental dalam hegemoni platform.
Organisasi seperti Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) dan Aliansi Driver Online mencerminkan apa yang Gramsci sebut sebagai “organic intellectuals” Intelektual organik yang muncul dari kelas pekerja sendiri untuk memformulasikan kesadaran kritis. Mereka tidak hanya menuntut kenaikan tarif, tetapi mengangkat pertanyaan yang lebih fundamental: mengapa manusia harus tunduk pada algoritma?
Pramoedya akan melihat perjuangan ini sebagai kelanjutan dari perlawanan Minke melawan sistem kolonial. Dalam Bumi Manusia, Minke belajar bahwa perlawanan dimulai dari penolakan untuk menerima definisi yang dipaksakan oleh penindas. “Saya bukan pribumi rendahan,” demikian Minke berkata. Kini, jutaan driver ojol berteriak, “Kami bukan algoritma data dalam kemasan kemitraan, kami manusia!”.
Kesadaran kelas terbentuk melalui pengalaman penindasan bersama. Ketika rating turun tanpa sebab jelas, ketika orderan tiba-tiba berkurang, ketika suspend akun tanpa mekanisme banding dalam momen-momen inilah driver ojol menyadari bahwa mereka menghadapi sistem, bukan sekadar persoalan individual. Dari kesadaran individual, lahirlah solidaritas kolektif.
Melawan Amnesia Digital. Žižekian Wake-Up Call
Pramoedya selalu menekankan pentingnya ingatan kolektif dalam melawan penindasan. “Jangan sampai kita menjadi bangsa yang amnesia,” pesannya. Dalam konteks digital, amnesia ini terwujud dalam bentuk normalisasi eksploitasi melalui teknologi.
Žižek akan menambahkan dimensi ideologis amnesia ini: kita tidak benar-benar lupa, tetapi kita melakukan “disavowal”, “Saya tahu driver ojol dieksploitasi, tapi saya tetap pakai aplikasi karena praktis.” Ini adalah mekanisme psikologis yang memungkinkan kita berpartisipasi dalam sistem eksploitasi sambil mempertahankan self-image sebagai orang baik.
Setiap kali kita memberikan rating rendah karena driver terlambat beberapa menit, kita berpartisipasi dalam sistem disiplin digital yang menghukum mereka. Setiap kali kita memilih driver termurah tanpa peduli kesejahteraannya, kita menjadi agen dari race to the bottom. Namun kita menyangkal tanggung jawab ini dengan berkata “Itu kan tugasnya platform, bukan saya.”
Gramsci akan melihat amnesia ini sebagai bagian dari hegemoni platform yang berhasil membuat konsumen merasa tidak bertanggung jawab atas kondisi kerja driver. Platform memisahkan “pengalaman konsumen” dari “realitas produksi,” sehingga eksploitasi menjadi tidak terlihat.
Perlawanan terhadap kapitalisme pengawasan dimulai dari menolak amnesia ini. Seperti yang dilakukan Pramoedya melalui tulisan-tulisannya, kita perlu mendokumentasikan dan menyuarakan pengalaman driver ojol sebagai bagian dari sejarah perjuangan kelas di era digital. Ini bukan hanya soal empati, tetapi soal mengungkap struktur eksploitasi yang tersembunyi di balik interface yang ramah.
Gatsu51
Staffsus Menaker RI